Sekali-kali ngrembug politik ah...mumpung masih menikmati bulan Ramadhan penuh berkah. Semoga kepedulian tentang masalah ini didengar oleh para elit politik beserta simpatisannya dengan hati terbuka dan ikhlas seikhlas kita menjalankan Puasa Ramadhan.
Saudara-saudara.....
Pemilu 2009 masih lama. Masa resmi kampanye juga belum dimulai. Tapi kita semua pasti tahu bahwa peristiwa itu pasti terjadi. Peristiwa kekerasan politik berupa tawuran antar pendukung partai politik yang telah mendarah daging dalam budaya politik di negeri kita. Adu fisik yang kadangkala harus mati konyol akan menjadi berita seru dua tahun lagi.
Untuk Jawa Tengah, sepertinya tidak perlu waktu selama itu karena kabarnya Pilihan Gubernur akan dilaksanakan tahun 2008. Sekarang saja spanduk-spanduk, stiker, serta baliho para calon Gubernur sudah mengawali panasnya suhu politik di Jawa Tengah.
Kalau kita amati lebih teliti, semenjak Pemilu 2004 hampir tiap tahun kita punya hajat politik baik di tingkat nasional maupun daerah. Diawali dari Pilihan legislatif, Pilihan Bupati, Pilihan kepala desa, lalu pilihan Gubernur dan balik lagi ke pilihan Legislatif begitu seterusnya. Kayak jadwal Liga Indonesia yang padat banget.
Kekerasan politik semacam ini cukup sering terjadi, terutama pada masa kampanye pemilu. Pada musim kampanye Pemilu 1999, misalnya, tidak sedikit kekerasan politik terjadi yang dilakukan oleh pendukung partai politik atas pendukung atau properti (kekayaan) partai politik lawannya. Bentuknya antara lain pembakaran dan perusakan gedung partai politik, bentrok fisik antar massa dan penghadangan terhadap ketua umum partai politik tertentu.
Bentrok antar massa partai politik adalah salah satu bentuk kekerasan politik. Kekerasan politik lainnya bisa berupa kekerasan internal partai, konflik antarpolitisi di parlemen, maupun kekerasan negara atas rakyat seperti yang dilakukan rezim otoritarian maupun ”rezim transisi”. Apa pun alasannya, kekerasan dalam politik Indonesia di era reformasi jelas telah mencederai demokrasi yang sedang dibangun di negeri ini.
Tiap menjelang masa (kampanye dan pencoblosan) pemilu di Indonesia, pertanyaan besar yang selalu muncul adalah soal kemungkinan timbulnya kekerasan politik. Kekerasan politik seolah – olah telah mentradisi di negara ini sejak bangsa ini merdeka. Sehingga tidak mengherankan bila setiap kali mendekati masa pemilu, masyarakat selalu dihantui oleh perasaan was-was akan kekerasan yang dilakukan oleh partai politik. Di lingkungan partai politik sendiri tak kalah was-wasnya. Mereka sejak dini telah menyiapkan kader-kadernya dengan pakaian mirip militer untuk berjaga-jaga bila ada tindak kekerasan atau intimidasi dari partai politik lainnya.
Masalah ''hantu kekerasan'' politik di masa pemilu bukan hanya terjadi setelah era Orde Lama. Di zaman Orba pun masalah itu muncul, terutama setelah terjadinya kekerasan politik yang dilakukan pendukung PPP pada masa kampanye pemilu tahun 1982 yang terkenal dengan insiden Lapangan Banteng. Di masa setelah Orba, soal hantu kekerasan makin menjadi ancaman ternyata karena instabilitas sosial yang begitu luas di seluruh belahan wilayah Indonesia.
Partai tertentu di beberapa kabupaten sudah melakukan provokasi dengan mencabut dan merusak atribut partai lain yang dipasang di daerahnya. Bahkan provokasi fisik yang menyerupai kekerasan juga dilakukan. Sekalipun hal itu terjadi pada skala yang sangat terbatas, tetap tidak bisa diabaikan hal itu bisa memicu kekerasan pada masa pemilu. Agaknya, kompetisi antarpartai yang begitu ketat, terutama karena adanya ketakutan di kalangan pendukung partai tertentu akan kemungkinan menurunnya perolehan suara, membuat para pendukungnya berada pada kondisi ketegangan yang tinggi, sehingga potensi kekerasan setiap saat bisa meledak.
Pengalaman traumatik kekerasan politik banyak dialami dialami masyarakat berkenaan dengan Pemilu. Di beberapa tempat seperti Jakarta pun kini mengalami hal yang sama setelah peristiwa kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan Mei 1998 benar-benar membuat masyarakat Jakarta trauma, sehingga mereka tidak lagi bereaksi terhadap provokasi yang terjadi.
Tetapi bukan berarti potensi kekerasan tidak ada lagi di Jakarta. Potensi ini muncul dari kelompok-kelompok sosial atas dasar etnis yang dibuat elite-elite politik Jakarta pada saat pemilihan gubernur beberapa waktu lalu. Salah satu organisasi berdasarkan kelompok etnis yang dulu dibuat oleh elite politik di Jakarta itu kini sudah menjelma menjadi semacam 'makhluk Frankenstein', sebuah hal yang diistilahkan oleh Pujastana. Suatu makhluk yang dibuat tetapi kemudian perilakunya tidak bisa dikendalikan oleh penciptanya. Anggota organisasi itu kini menjadi preman-preman politik yang menjadi ancaman bagi kestabilan sosial di daerah-daerah pinggiran Jakarta.
Agaknya sudah menjadi diktum, bahwa sebuah kelompok yang dibuat untuk tujuan-tujuan politik jangka pendek hanya akan menjadi makhluk Frankenstein di kemudian hari yang malah menjadi masalah bagi pembuatnya.
Pemilu 1999
Bukan hanya di Jakarta terjadi kekerasan menjelang pemilu 1999. Di daerah juga terjadi hal yang sama. Di Banjarmasin contohnya. Tahun 1997 terjadi kekerasan antara pendukung Golkar dan PPP yang menurut, pengamat politik Indonesia, Donald K. Emmerson, menelan sekitar 100 nyawa. Pada tahun 1999 itu pula meletus kekerasan antar pemeluk agama di Poso dan Ambon.
Karena kenyataan itu pula, maka ketika pemilu 1999 berlangsung, kekerasan politik antara pendukung parpol dipastikan akan terjadi.
Anehnya, pemilu 1999 yang disebut pemilu paling demokratis selama 44 tahun terakhir, justru berlangsung nyaris tanpa kekerasan. Bahkan di Ambon, di mana kekerasan antara pemeluk agama mencapai puncaknya tahun 1999, masa kampanye pemilu dan hari pencoblosan berlangsung tanpa insiden.
Tidak banyak yang tahu kenapa kekerasan justru menghilang pada masa pemilu 1999 itu. tetapi Donald K Emmerson, dalam bukunya, Indonesia Beyond Soeharto, memperkirakan partai peserta pemilu berusaha menahan diri sebegitu rupa karena berharap akan memperoleh suara dan kursi di mana kekerasan politik yang muncul akan menyebabkan terganggunya harapan itu. Atau juga karena tanggung jawab nasional di kalangan masyarakat lebih kuat dari yang diduga.
Demokrasi di negara-negara yang demokrasinya belum stabil pemilu selalu menjadi hantu kekerasan bagi warganya. Masalahnya akan jadi lebih rumit apabila demokrasi yang belum stabil disertai dengan tingkat diferensiasi sosial yang tingi. Hampir seluruh negara berkembang dihadapkan pada soal ini. Sekalipun suatu negara (berkembang) telah mengalami proses transisi yang lama dari pemerintahan otoriter menuju demokrasi, tetapi kekerasan politik masih menjadi soal yang pelik.
Misalnya, Kawasan Amerika Latin, yang telah lebih dulu memasuki masa transisi menuju demokrasi di pertengahan tahun 1980-an, pemilu masih menjadi momok yang menakutkan sampai sekarang. Pemilu lalu tidak menjadi celebration of democracy sebagaimana layaknya di negara-negara yang demokrasinya stabil, melainkan lebih menyerupai agony of democracy. Di Kawasan tertentu benua Afrika hal yang sama juga terjadi.
Hal ini karena negara-negara yang demokrasinya belum stabil itu, semua lembaga negara mengalami tingkat politisasi yang tinggi. Tidak ada suatu perangkat demokrasi yang established sehingga perebutan posisi dalam lembaga-lembaga negara tidak menjadi suatu kompetisi yang fair dan bisa dianggap wajar. Karena soal politisasi ini belum bisa diatasi di banyak negara berkembang, maka jarang sekali masa depan demokrasi di kawasan itu dilihat dengan optimis. Selalu terdapat kemungkinan besar sistem demokrasi akan berumur singkat dan otoritarianisme kembali merajalela.
Akan halnya Indonesia, banyak pengamat politik melihat bahwa sangat kecil kemungkinan bahwa Indonesia akan mundur dari sistem demokrasi untuk kembali ke sistem otoriter. Tetapi jika kemungkinan kekerasan politik dan persaingan kepentingan tidak bisa dikelola dengan baik, maka selalu terbuka jalan bagi Indonesia untuk kembali sistem otoriter.
Akar Kekerasan Politik Di Indonesia
Pertama, terjadi penyederhanaan dan pembatasan partai politik dengan segala konsekuensinya, umumnya dalam kehidupan demokrasi dan secara khusus dalam kaitan dengan pendidikan politik. Dengan cara ini kebebasan berpartai, berorganisasi dan kesempatan melakukan pendidikan politik dalam kerja organisasi politik riil menjadi dibatasi dan dikebiri. Bahkan, lebih dari itu, seluruh semangat demokrasi dimatikan karena tidak ada perbedaan pandangan, saling kontrol antar partai, tidak ada pengajuan calon pemimpin tandingan dan seterusnya, sebagaimana kita alami semua pada waktu itu. Itu dilakukan demi pragmatisme ekonomi agar tujuan pembangunan ekonomi bisa dicapai tanpa gangguan stabilitas politik oleh mekanisme demokrasi politik formal.
Kedua, dalam alur yang sama kecuali Golkar, parpol yang lainnya tidak dimungkinkan untuk melakukan apa yang idealnya dikerjakan sebuah partai yang sehat, yaitu pendidikan politik bagi para kadernya untuk menyiapkan dan mencekal calon pemimpin partai dan pemimpin bangsa. Jangankan kaderisasi, rapat partai-partai saja dikejar-kejar, diawasi dan diintimidasi aparat negara. Apa yang bisa dilakukan untuk pendidikan politik kader partai dalam kondisi seperti itu?
Jadi, kalau politisi yang dihasilkan parpol sekarang adalah seperti ini, harus kita akui bahwa itulah buah dari proses kehidupan politik tanpa pendidikan politik dalam parpol. Tidak ada pemimpin hebat yang bisa dihasilkan parpol karena tidak ada pendidikan politik, baik itu formal dalam bentuk kaderisasi maupun dalam bentuk berorganisasi secara wajar. Padahal, berorganisasi secara wajar termasuk belajar menyelesaikan konflik diantara kader, adalah pendidikan politik paling riil. Tetapi, itu tidak ada karena yang ada adalah belajar menghindari dan berkelahi dengan aparat, yang berarti belajar menggunakan otot dan kekerasan.
Ketiga, secara lebih luas juga harus kita akui hampir tidak ada kebebasan berorganisasi secara sehat dan wajar, tempat tokoh-tokoh muda, calon pemimpin bangsa bisa melakukan penggemblengan dan pendidikan dirinya sebagai politisi dan pemimpin bangsa. Berbagai aktivitas berorganisasi dihalangi atau harus melalui prosedur perizinan yang berlaku, kecuali harus dilakukan secara underground, . Dan, kalau tertangkap, segala idealisme murni mereka demi kemajuan bangsa diberangus dan dimatikan dengan segala intimidasi dan tindak kekerasan bahkan dengan restu negara.
Pemilu 2009 dan seterusnya kita berharap peristiwa kekerasan pada waktu kampanye tidak lagi terjadi. Ini akan melahirkan pembodohan politik (political ignorance), yang entah jilid keberapa lagi, ditengah-tengah bangsa ini membutuhkan pendidikan politik yang sehat dan dinamis pada masyarakat. Pemilu hendaknya menjadi titik awal partai-partai untuk lebih dapat memberikan pendidikan politik yang sehat bagi masyarakat. Bukan memberikan celah-celah untuk melakukan tindakan kekerasan atas nama demokrasi. Bila pendidikan politik yang sehat itu terlaksana dengan baik, banyak keuntungan yang bisa kita petik.
Kita tinggal lihat pesta politik masa mendatang apakah rakyat masih saja Bodoh atau sudah lebih cerdas dalam berpolitik.
Kalau kekerasan itu masih saja terjadi, maka tidak mengherankan bila Pemilu mendatang akan lahir manusia-manusia apatis yang enggan menggunakan hak pilihnya di bilik suara. Bagaimana menurut Anda? Jangan2 anda sudah ancang2 mau Golput juga















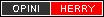

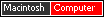


0 comments:
Post a Comment